
Web Sosial Anak Asuh YKMM
Yayasan Kerta Mentas Mandiri
Posted by : admin, pada : 20 Januari 2017, Dibaca 381 kali
Tweet

Masyarakat Indonesia tengah dihantui oleh maraknya kabar bohong, atau biasa kita sebut hoax. Menurut kamus Merriem Webster versi daring, hoax adalah (1) sebuah perbuatan yang bertujuan mengelabui atau membohongi, dan (2) menjadikan sesuatu sebagai kebenaran umum melalui fabrikasi dan kebohongan yang disengaja. Melalui jejaring media sosial dan internet, hoax menyebar tanpa bisa dicegah. Tidak saja memicu kemarahan dan kebencian terhadap pihak lain, lebih jauh, hoax mengancam persatuan dan ideologi bangsa ini.
Dari pemerintah hingga lapisan masyarakat bersama-sama menggalang kekuatan untuk melawan hoax. Beragam cara dilakukan. Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax dideklarasikan dan melakukan sosialiasi di enam kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang, Bandung, dan Wonosobo. Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga melakukan sosialisasi penangkalan hoax selama enam bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga memblokir hampir 800 media yang sering memproduksi hoax. Aplikasi telepon seluler bernama “Turn Back Hoax” pun dikembangkan. Aplikasi ini berisi aduan dan konfirmasi tentang informasi yang diduga hoax. (Kompas, 9 Januari 2017)
Hanya saja, cara-cara tersebut masih sebatas permukaan. Upaya melawan hoax masih dalam tahap seremonial, belum secara struktural dan kultural. Masyarakat kita telah terbiasa dengan pola penerimaan informasi secara mentah-mentah. Nalar kritis dan skeptis belum terbentuk secara menyeluruh. Padahal, lemahnya nalar kritis dan skeptisme itulah yang menjadi akar berkembang biaknya hoax di masyarakat.
Lemahnya nalar kritis dan skeptisme masyarakat terhadap suatu informasi hoax disebabkan oleh keterikatan identitasnya, baik identitas ras, suku, agama, hingga afiliasi politik. Adanya keterikatan identitas menyebabkan orang buta dan tuli pada kevalidan sebuah informasi. Segala informasi yang membela identitas dirinya dipercaya sebagai kebenaran tanpa menimbang apakah hal itu hoax atau bukan.
Kita bisa menengok kasus yang terjadi dalam konflik agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aparat kepolisian gagal meredam akar konflik yang sebenarnya sepele karena hoax lebih cepat tersebar luas dan dikonsumsi masyarakat. Saat itu, situs media yang berafiliasi dengan salah satu agama berhasil mengobarkan api kemarahan dan kebencian terhadap agama lain sehingga terjadilah kerusuhan dan pembakaran tempat ibadah.
Pemblokiran beberapa media tidak bisa menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya struktural dan kultural sedari dini agar nalar kritis dan skeptisme masyarakat meningkat. Lembaga pendidikan punya andil besar dalam hal ini. Lembaga pendidikan menjadi tempat untuk melakukan pembudayaan nalar kritis dan skeptisme dalam tradisi akademik-ilmiah-empiris. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih belum mampu membudayakan hal itu kepada setiap peserta didiknya.
Metode belajar sekolah yang masih berkutat pada hafalan dan ujian, tidak menyediakan ruang bagi pengembangan nalar kritis dan skeptisme. Peserta didik lebih rajin menghafal, namun miskin dalam membangun kerangka berpikir kritis terhadap suatu masalah. Peserta didik dikondisikan dalam kurikulum yang tidak memberikan ruang bagi alternatif jawaban dan kebenaran. Pendidikan kita sekadar menjadi alat transfer kebenaran dari guru ke siswa, bukan medium pembangunan nalar kritis dan ilmiah dalam bingkai kesetaraan.
Hal tersebut berbeda jauh dengan negara-negara maju. Pendidikan Jerman misalnya, sedari usia dini telah membuat program khusus untuk mengembangkan nalar siswa. Sejak dekade 1960-an, Jerman membuat program bernama Kinder Philosophieren, atau “anak-anak berfilsafat”. Program ini mengadopsi gaya berpikir filsafat, yakni dengan membiasakan siswa mengajukan beragam pertanyaan dari pelbagai sudut pandang. Peserta didik didorong untuk mempertanyakan kebenaran dari suatu informasi secara mendalam.
Maugh Gregory (dalam Wattimena, 2016: 166) menunjukkan, bahwa program ini banyak membantu anak-anak. Mereka bisa mengajukan pertanyaan dan menemukan sudut pandang berbeda melalui diskusi-diskusi yang dilaksanakan. Program tersebut merangsang pikiran siswa melalui percakapan-percakapan bermutu dan menggoda siswa menyusuri pengetahuan baru. Anak-anak diajak melampaui identitas sempitnya dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang orang-orang yang berbeda. Pemahaman antar budaya, antar agama, dan antar kelas sosial bisa tercipta melalui program ini. Program ini digunakan sebagai upaya untuk melampaui fundamentalisme dan fanatisme yang menjadi pemicu mudahnya hoax merebak.
Perbaikan dunia pendidikan memang membutuhkan waktu yang lama. Namun, hasilnya akan lebih kuat dan menebas akar masalah. Sesering apa pun dilakukan sosialisasi, secanggih apa pun aplikasi dan teknologi dikembangkan, segarang apa pun pemerintah memblokir situs hoax, hasilnya akan tetap sama jika akarnya tidak pernah dicabut. Hoax akan kembali berkembang biak seiring iklim politik dan kehidupan sosial yang setiap saat bisa memanas. (tribunjateng/cetak)
Sumber: jateng.tribunews.com
Kategori :





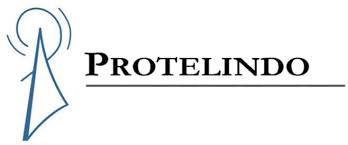




- IP Anda : 216.73.216.98
- Browser Anda : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

1.jpg)









